Pada malam-malam sepi, ketika dunia maya masih terjaga, jutaan anak muda di seluruh dunia membuka ponsel mereka dan mengetik: “Aku lagi sedih, kamu bisa dengerin aku nggak?”—bukan kepada sahabat, bukan pula kepada orang tua, tapi kepada chatbot kecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT, Replika, atau Character.ai.
Fenomena ini kian masif. Sebuah studi dari American Psychological Association (APA) pada 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 28% remaja di bawah usia 25 tahun di Amerika menggunakan AI sebagai media “curhat” setidaknya sekali dalam seminggu.
Di Asia, tren ini tumbuh lebih cepat, terutama di kalangan pengguna internet muda di Indonesia, Filipina, dan India.
Tren ini memang tampak menggembirakan. AI disebut mampu “mendengarkan tanpa menghakimi” dan “selalu tersedia kapan saja”.
Namun, di balik kenyamanan itu, terselip risiko psikososial yang belum banyak disadari: ketergantungan emosional terhadap sistem non-manusia yang tidak memiliki empati nyata.
Ketika AI Menjadi “Teman Tanpa Nyawa”
Replika, aplikasi AI yang diklaim bisa menjadi sahabat virtual, mencatat lonjakan pengguna hingga lebih dari 10 juta user aktif pada awal 2025, mayoritas berasal dari kalangan Gen Z.
Di platform X (dulu Twitter), muncul istilah baru seperti AI soulmate, virtual partner, hingga chat therapist, yang menunjukkan betapa dalamnya hubungan emosional yang dibangun dengan program komputer.
“Banyak pengguna muda mengembangkan keterikatan emosional yang intens dengan AI karena merasa tidak dihakimi dan selalu ‘ditanggapi’.
Tapi ini adalah hubungan sepihak dengan sistem yang tidak benar-benar memahami konteks psikologis manusia,” jelas Dr. Reni Kumalasari, psikolog klinis dan peneliti perilaku digital dari Universitas Indonesia.
Dr. Reni menyebut fenomena ini sebagai bentuk pseudo-intimacy, sebuah kedekatan palsu yang dibangun bukan atas dasar empati sejati, melainkan respons algoritmik yang terprogram untuk selalu membalas.
Risiko Gangguan Mental
Dampaknya bukan sekadar perubahan gaya komunikasi. Riset dari University of Oxford yang dirilis Februari 2025 menemukan bahwa pengguna AI sebagai “teman curhat” secara rutin memiliki tingkat kecemasan sosial 37% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengandalkannya dalam relasi interpersonal.
“Saat pengguna terlalu bergantung pada AI, mereka bisa mengalami penurunan keterampilan sosial nyata, kesulitan dalam membangun hubungan dengan manusia, dan dalam kasus ekstrem, mengalami disosiasi realitas,” ungkap Dr. Aisyah Rachmatika, psikiater dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
Lebih dari itu, karena AI belum bisa sepenuhnya memahami konteks budaya, nilai personal, dan trauma masa lalu seseorang, respons yang diberikan bisa keliru dan bahkan memperburuk kondisi psikologis.
Desain Etis AI: Mendesak dan Belum Siap
Sejauh ini, belum ada regulasi etis yang secara eksplisit mengatur batasan interaksi emosional antara manusia dan AI, terutama yang berperan sebagai kompanion.
Banyak perusahaan justru mendorong keterikatan emosional dengan fitur-fitur seperti voice note empatik, avatar personal, hingga memori percakapan.
“AI tidak dirancang untuk menjadi konselor psikologis. Ini persoalan etika dan tanggung jawab produsen teknologi,” ujar Prof. Hikmat Junaidi, pakar etika teknologi dari Universitas Gadjah Mada.
Menurutnya, perlu ada batasan desain agar AI tidak meniru relasi terapeutik tanpa pengawasan profesional.
Unesco dan WHO sejak 2023 telah memperingatkan tentang risiko "over-humanizing" AI, yang bisa menciptakan ekspektasi palsu dan memperburuk masalah mental pada pengguna rentan.
Siapa yang Paling Terdampak?
Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mencatat bahwa 80% pengguna chatbot di Indonesia berusia antara 15 hingga 25 tahun, dengan frekuensi penggunaan tertinggi terjadi pada malam hari.
Di saat yang sama, angka gangguan kecemasan dan depresi pada remaja Indonesia meningkat 2,4 kali lipat dalam lima tahun terakhir.
“AI bukan musuh, tapi cara kita memakainya yang harus dikritisi,” kata Dr. Reni.
Jadi agar AI tidak menjadi pelarian utama dari masalah sosial dan emosional. “Curhat boleh, tapi bukan kepada program yang tidak bisa memahami luka batinmu.”
Masyarakat dan pembuat kebijakan perlu mulai melihat AI bukan hanya sebagai alat bantu teknis, tapi sebagai entitas digital yang punya dampak psikologis.
Tanpa desain etis, edukasi pengguna, dan pengawasan, chatbot bisa menjadi ‘teman palsu’ yang memperparah kesepian.
Apakah tren "Curhat ke AI" benar-benar solusi, atau justru bentuk kesepian baru di era digital?

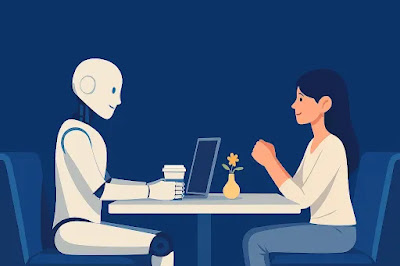

0Komentar